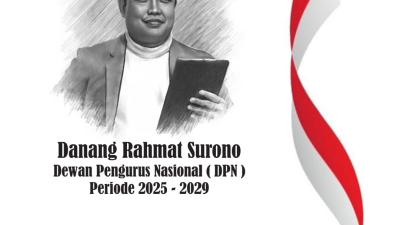Oleh: Agus Sutawijaya.
(CIO) — “Man, bangunlah…. itu Uci datang,” bisik ku perlahan ke telinga sahabatku.
Air mataku meleleh, menatap tubuh yang tergeletak di sampingku. Sahabatku yang dulu penuh semangat, dan selalu membuat siapa saja senang jika berada di sampingnya, kini terbaring lemah tak berdaya. Berbagai macam kabel terpasang di tubuhnya. Tubuh atletisnya kini hanya tinggal kulit pembalut tulang. Matanya cekung, terpejam, namun sesekali meneteskan air mata. Kadang, bibirnya bergetar melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran, kadang memanggil almarhum Mak namun lebih sering ia menyebut satu nama, Uci.
Herman adalah sahabat baik ku, kuanggap abang karena ia lebih tua dua tahun dariku. Kami bertemu dua tahun yang lalu di sebuah pengajian di Masjid Sunda Kelapa, mengaku baru saja datang dari Sumatera, dan belum punya tempat tinggal di ibu kota.
Ia adalah lulusan terbaik salah satu kampus ternama di Sumatera Utara dengan jurusan Sastra Jepang. Herman juga adalah seorang yang menyenangkan, dewasa dan tentu saja alim. Setahuku, ia adalah seorang Hafidz, entah berapa juzz, tapi yang pasti hapalannya sangat banyak. Jika ia bicara, maka segera ia akan jadi pusat perhatian. Bukan karena wajahnya yang rupawan, namun juga tata bahasanya yang sangat sopan dan indah. Jujur, aku selalu kagum padanya.
Namun, dibalik semua keceriaannya, aku tahu ia menyimpan beban yang sangat berat, entah apa itu. Hampir setiap tengah malam, ia selalu menangis dalam sujud-sujud panjangnya. Di rumah, ia lebih senang menenggelamkan harinya dengan membaca kitab suci dan puluhan koleksi buku, yang semakin hari semakin bertambah jumlahnya.
Ku perhatikan tiga bulan terakhir kondisinya semakin menghawatirkan. Kesehatannya menurun drastis. Bermalam-malam ia tak lagi bisa tidur. Ia juga tak lagi banyak bicara, hanya terbaring, tatapan matanya kosong. Berulang kali ku coba bicara, sekedar berbagi, atau mengajaknya keluar untuk berobat, namun Herman hanya diam. Sampai pada saat aku pulang kantor, kutemukan ia tergeletak di lantai tak sadarkan diri. Segera ia kubawa ke RS Siloam dan disinilah kini ia berada. Di ruangan penuh alat bantu hidup, dengan bunyi alarm tak berhenti. Tak boleh ditunggui, kecuali pada jam tertentu aku boleh masuk untuk melihatnya sejenak.
Ketika merapikan kamarnya, kutemukan sebuah buku harian. Di dalamnya kutemukan jawaban apa yang membuat baikku yang penuh gairah dan selalu memotivasi itu seolah kehilangan ruhnya. Seorang wanita telah merebut hati dan jiwanya, dan kini ia kehilangan segalanya, juga semangat hidupnya.
Boleh disambung besok aja gak? Kepala sakit banget…
Ditulis di kamar 519 bed 2 dengan tangan diinfus dan kepala serasa nyaris putus.
(***)