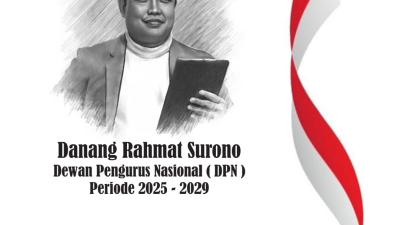Oleh: Agus Sutawijaya
Lakon 2
Golau
Untuk sementara waktu kami sekeluarga tinggal di kediaman Tuok Sanuki. Beliau adalah orang tua dari Pak Dul, teman ayah, yang membawa kami ke kampung ini. Usia Tuok Sanuki sekitar 65 tahun. Tubuhnya tinggi, berperawakan sedang. Sehari-hari ia senang menggunakan sarung dan kaus oblong. Alis matanya tebal. Sejak istrinya meninggal tahun lalu, ia tampak selalu murung. Wajahnya tampak sedih. Ia sering menghabiskan waktu dengan duduk di beranda rumah panggung, sambil membaca Al Quran. Tatap matanya tajam namun kosong. Ada ruang hampa di sana. Ada kerinduan yang dalam. Kerinduan akan istri yang setia mendampingi yang kini telah pergi. Kerinduan akan kampung halaman.
Tuok Sanuki sebenarnya perantau seperti juga kami. Ia juga berasal dari Jawa Barat. Aku tak tahu persis dari mana beliau berasal. Ia telah merantau sejak muda belia. Bekerja di perusahaan kontraktor Caltex di daerah Rumbai, kemudian berjodoh dengan orang Tanjung Rambutan. Sejak pergi merantau Tuok Sanuki tak pernah sekali pun pulang ke kampung halamannya. Kerinduan itulah yang ditanggungmya selama ini. Untunglah, kehadiran kami sekeluarga bisa sedikit mengobati kerinduannya. Binar matanya kembali setiap kali ia berbicara dengan ayah menggunakan bahasa sunda. Bahasa ibunya.
Seperti lazimnya rumah di kampung ini, rumah Tuok Sanuki juga merupakan rumah panggung yang terbuat dari kayu. Rumahnya termasuk besar dibandingkan rumah lainnya, wajar saja, karena semasa muda Tuok Sanuki termasuk orang berada. Di bagian depan rumah terdapat sebuah beranda yang cukup luas. Di sanalah biasanya beliau duduk, di atas sebuah kursi kayu beranyam rotan.
Di sebelah kanan rumah terdapat sebuah pondok kecil. Bangunan ini adalah sebuah warung papan yang lama tak digunakan. Di sanalah kami sekeluarga akhirnya tinggal. Mak berencana akan berjualan penganan kecil, sebab di sebelahnya ada Sekolah Dasar. Di sekolah itu pula akhirnya aku mendapatkan ijazah pertamaku setelah berpindah sekolah sebanyak tiga kali. Di sekolah ini pula aku pertama kali berkenalan dan mendapat sahabat.
Banyak hal menarik dari kampung ini, salah satunya adalah kebiasaan mereka melafalkan nama dengan sebutan khas atau memberi “Golau” atau gelar sesuai keadaan fisik atau kejadian tertentu. Saking lekatnya panggilan itu maka kebanyakan orang tak kenal jika kita sebutkan nama aslinya. Mereka baru “ngeh” ketika kita sebutkan “Golau” nya.
Sebut saja salah satu sahabatku, nama aslinya adalah Helmawati, tapi di kampung orang memanggilnya Kohel. Bahkan, si empunya nama pun terkadang lupa nama aslinya sendiri. Pernah saat di kelas, Udo Nopi, wali kelas kami mengabsen seluruh murid. Nama yang terpanggil mengacungkan tangan dan menyebut hadir. Saat namanya dipanggil, sahabatku ini diam saja…
“Helmawati..!!” Seru Udo Nopi, namun sang pemilik nama hanya diam saja…
“Kohel..!!” Udo Nopi kali ini memanggil dengan nada suara sedikit lebih tinggi, dan ajaibnya sahabatku langsung mengacungkan tangan..
“Hadir Do…” jawabnya tak kalah lantang, dan kami semua tertawa.
Ada juga kawan-kawan yang dipanggil dengan sebutan berdasarkan kondisi tubuhnya, Iwan Bincik misalnya, nama aslinya adalah Muhammad Ridwan, namun karena tubuhnya kontet kurang gizi, jadilah ia dipanggil Iwan Bincik. Atau Iwan yang lainnya, dipanggik Iwan Bocek, karena kakinya yang bersisik seperti ikan Bocek atau ikan Gabus, dan baunya jika siang hari, persis bau “Bocek Bajomu”.
Aku tak ingat ada berapa nama Iwan yang ku kenal, banyak. Ada Iwan Togai, karena tubuhnya yang tinggi, ada pula Iwan Tuyuok, dipanggil demikian karena telinganya “batuyuok”. Tuyuok bahasa Indonesianya Congek, atau bahasa medisnya disebut dengan otitis media supuratif kronis (OMSK), adalah peradangan kronis pada telinga bagian tengah yang disertai dengan pecahnya (perforasi) gendang telinga. Penderitanya akan mengalami keluarnya cairan berbau dari telinga secara terus-menerus atau hilang timbul. Dulu banyak anak-anak terkena penyakit ini, sehingga di kelas ketika matahari mulai beranjak naik, aromanya pun mulai mengganggu penciuman.
Ada pula yang dipanggil Iwan Kincik, sebab waktu kecil ia selalu berak di celana. Menurut analisaku sebagai anak-anak kala itu, sebutan atau Golau itu juga digunakan sebagai pembeda sebab nama panggilan kami banyak yang sama.
Ada lagi yang khas tentang sebutan atau panggilan di kampung kami. Sebagian orang bahkan tidak dipanggil dengan nama mereka, melainkan dengan panggilan kesayangan. Untuk laki-laki panggilan kesayangan di sini adalah Buyuong dan Ujang, sedang untuk perempuan biasanya dipanggil Gadi. Di sinilah peran Golau sangat berarti. Sebab tanpa adanya Golau, orang tak tahu Buyuong, Ujang atau Gadi yang mana. Jadilah setelah nama Buyuong atau Ujang menjadi identitas mereka.
Ada Buyuong Kenek, karena ia paling kecil. Ada Ujang Gereba, dikenal karena setiap kali menyebut Setir, ia selalu menyebutnya Gereba. Ada juga Ujang Cawik, sebab ia suka sekali bercarut atau mengumpat. Dan Ujang lainnya.
(***)