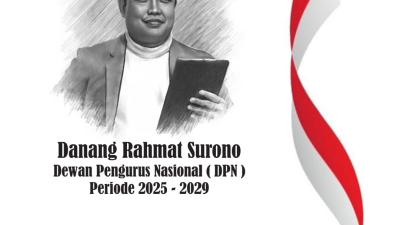Oleh : Agus Sutawijaya
Lakon 1
Negeri Baru
Hari beranjak senja, ketika mobil angkutan umum yang kami tumpangi berhenti di depan sebuah kedai di pinggir jalan nasional. Setelah menurunkan semua barang bawaan Ayah lalu membayar sejumlah uang sebagai ongkos kepada kernet yang kemudian kuketahui di daerah ini di sebut “Sitokar”, dan angkutan yang kami tumpangi di sini disebut “Superband”.
Beberapa orang yang saat itu nampak sedang duduk di kedai di pinggir jalan menatap kami dengan heran. Aku masih terduduk di atas kardus barang bawaan kami, kesadaranku belum sepenuhnya pulih. Rasa kantuk dan sakit kepala akibat mabuk perjalanan masih membebani kepalaku. Mak berdiri menenteng kantong kresek berisi pisang rebus bekal perjalanan kami. Dipelukannya tertidur adik ku nomer tiga, Ria. Usianya baru delapan bulan kala itu. Sementara adik ku seorang lagi sibuk memainkan bonekanya. Sebuah boneka plastik berbaju merah berenda dengan rambut pirang. Matanya berwarna biru, jika diletakkan dalam posisi berdiri, matanya secara ajaib akan terbuka, dan jika dibaringkan mata biru boneka itu akan berputar dan terpejam. Erni nama adikku nomer dua. Ia cantik, dengan pipi tembam dan rambutnya yang panjang. Hari itu Mak mengikat rambutnya menjadi jalinan kepang yang indah dengan pita berwarna merah jambu dan sebuah bando berwarna senada.
Ayahku berjalan menyeberangi jalan raya dan menuju ke kedai tempat beberapa orang lelaki duduk tadi. Nampak ia berbincang dengan seorang lelaki setengah baya. Entah apa yang mereka bicarakan, kami hanya memandangi dari seberang jalan saja. Sejurus kemudian, Ayah kembali ke tempat kami berada. Bersama kami menyeberang menuju kedai tadi. Sementara ayahku, berulang kali kembali ke seberang jalan untuk menjemput barang bawaan kami yang masih tertinggal di pinggir jalan.
Ibu pemilik kedai menyuguhi kami teh hangat dan mempersilahkan Mak untuk minum.
“Minumlah kak,…….” ucapnya kepada Mak, selebihnya kami tidak mengerti lagi apa yang diucapkan oleh ibu pemilik warung tadi, aku menduga itu adalah bahasa daerah sini, bahasanya unik, enak didengar dengan banyak akhiran “O” di setiap katanya.
“Terimakasih bu” Mak menjawab seraya tersenyum.
Ayah nampak membantu seorang lelaki setengah baya menaikkan barang bawaan kami ke atas sebuah sepeda motor bebek berwarna merah. Aku tahu mereknya Yamaha, dari tulisan yang tertera di bodi samping dan tercetak pada bagian mesin motor itu. Ketika dihidupkan, dari knalpotnya asap mengepul tebal bergulung-gulung persis mesin pembasmi nyamuk yang dihidupkan oleh petugas dari Dinas Kesehatan, dan motor itu perlahan bergerak meninggalkan kami. Tiga kali motor itu bolak-balik mengangkut barang bawaan kami, dan setelah kembali aku melihat Ayah memberikan sejumlah uang kepada bapak pemilik motor seraya mengucapkan terimakasih.
Setelah menghabiskan teh hangat yang disuguhkan ibu pemilik warung, kami berpamitan. Mak memberikan sebungkus wajik ketan kepada ibu kedai sebagai ucapan terimakasih dan kami pun beranjak dari kedai itu. Mak berjalan menggendong Ria dan menenteng plastik hitam. Ayah menggendong Erni yang sibuk dengan bonekanya di bahunya, ia selalu gembira setiap kali ayah menggendongnya di pundaknya. Sementara aku, tercepuk-cepuk berjalan dengan masih menahan sisa mabuk darat yang masih memenuhi kepalaku. Sepanjang perjalanan tadi, tak terhitung berapa kali aku muntah. Sungguh perjalanan yang sangat melelahkan.
Hari telah menjelang maghrib ketika kami mulai berjalan meninggalkan kedai tadi. Kami melewati jalan menurun di pinggir jalan aspal dan berbelok ke kiri. Sebuah jembatan kayu panjang dengan atap seng nampak membentang di atas sebuah sungai yang lumayan besar. Dipangkal jembatan nampak beberapa anak seusiaku duduk pada dua balok semen. Mereka semua memandang heran ke arah kami. Panjang jembatan itu sekitar 200 meter. Aku terkagum-kagum memandangi sungai dan seluruh pemandangan senja itu. Bias cahaya matahari yang berwarna jingga nampak sangat indah terpantul dari permukaan air yang bening. Tampak beberapa anak dan orang dewasa mandi dan berenang di pemandian sungai yang terletak di depan masjid di seberang jembatan sana. Kami bersama berjalan perlahan di atas jembatan itu, setiap kali menatap ke bawah ada perasaan gamang. Tiang jembatan itu tampak cukup tinggi, sekitar 6 meter kurasa. Airnya mengalir tenang. Ada beberapa petakan seperti “tambak” di sepanjang pinggir sungai, dugaanku, pastilah itu tempat nelayan membudidayakan ikan.
Di ujung jembatan, jalan menyimpang, di sebelah kiri aku melihat sebuah masjid besar. Ada sebuah papan tersandar miring di dinding masjid, tertulis “Masjid Tajrid Tanjung Rambutan”.
“ooh, Tanjung Rambutan….” gumamku pada diri sendiri, aku menduga itulah nama negeri tempat kami berada saat ini.
Sepanjang perjalanan tak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibir kami. Aku, asyik dengan pemandangan negeri baru ini, Erni adikku asyik menikmati sensasi terlonjak-lonjak di atas bahu kekar ayahku. Mak nampak cemberut, sedangkan Ria adik kecilku tak bicara apa-apa sebab ia masih terlalu kecil dan memang belum bisa bicara.
Perjalanan ini memang tak disetujui Mak, ia ingin kami sekeluarga kembali saja ke Lampung atau langsung kembali ke Bandung, tapi Ayah bersikeras membawa kami kemari.
“Percayalah mah, kalau kita pindah ke Lampung, aku khawatir akan perkembangan anak-anak, aku ingin anak-anak mengenal agama dengan baik” ucap Ayah meyakinkan Mak semalam sebelum keberangkatan kami. Oh iya, Ayah dan Mak memanggil dirinya masing-masing Mamah dan Papah, seperti itu sejak dulu awal mereka berumah tangga. Dulu aku memanggil Ayahku dengan sebutan Papah, namun karena seluruh lingkungan memanggil Mak dan Ayah, kami pun ikut-ikutan memanggil Ayah dan Mak, namun Ayah dan Mak tak pernah bisa merubah panggilan mereka satu sama lain.
“Kemana lagi Pah, belum cukupkah penderitaan kita selama tiga tahun ini, kenapa kita tidak pulang saja ke Bandung?” protes Mak sambil menangis.
Ayah meyakinkan bahwa negeri yang kami tuju adalah negeri yang ideal untuk kami tumbuh. Di sana semua orang shalat di masjid, terangnya. Tak ada satu anak pun yang tidak mengaji.
“Di kampung itu semua orang taat beribadah, anak-anak harus diajarkan agama dari awal, jangan sampai mereka seperti kita” Ayah berargumen.
“Kampung itu juga sangat subur, makanan berlimpah di sana, tumbuhan buah-buahan banyak, ikan melimpah dan masyarakatnya ramah” Ayah meyakinkan, Mak masih terdiam dalam isaknya, dibaringkannya adikku pada sebuah tikar pandan, malam pun berlalu, dan di sinilah kini kami berada kini, berjalan di sebuah negeri baru yang indah, negeri yang subur dan tenteram. Aku melihat anak-anak sebayaku berjalan bersama menuju masjid. Tangan kanan mereka memegang Al Quran, dan tangan kirinya memegang ikatan daun kelapa kering. Nampak mereka sangat bahagia. Dan aku tak sabar untuk bergabung dengan mereka.
(***)