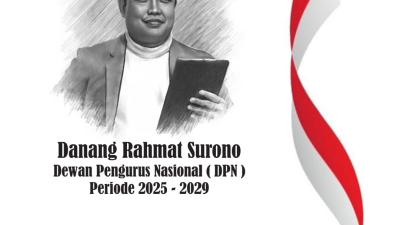Oleh : Agus Sutawijaya.
(CIO) — Sulit menggambarkan bagaimana sakit hatiku saat ini. Perpaduan antara cinta yang nestapa dan perih bak luka teriris sembilu.
Amel namanya. Gadis yang telah membuatku terluka. Putri salju anak Koh Aseng tukang gigi Garuda itu tiga hari yang lalu telah membuat hatiku berkecai. Cintaku ditolak mentah-mentah.
Aku pertama kali melihatnya saat aku masih kelas dua SD. Mak membawaku ke Koh Aseng setelah semalaman tak tidur karena gigi gerahamku yang berlubang meradang, sakit luar biasa.
Gadis kecil berkulit putih bak pualam itu keluar dari balik gorden membawakanku secangkir air hangat untuk berkumur. Jarinya yang kecil dan lentik berkuku mengkilat dan rapi. Pertanda ia anak yang memperhatikan kebersihan. Disela rasa sakitku yang timbul tenggelam, efek bius yang akan segera berakhir, aku melihat jemariku. Sepuluh jari keras berbuku, dengan kuku menyembul hitam berdaki. Kusembunyikan kedua tanganku di balik baju bergambar lelaki tampan dengan poni mungil berbentuk huruf “S”. Superman, jagoanku.
Amel siang itu memakai baju khas Tionghoa berwarna merah dengan motif naga berwarna emas. Rambutnya sebahu diikat ekor kuda. Poninya bagus disibak ke kiri. Di telinganya mengantung anting-anting dari perak. Indah.
Kutaksir ia pastilah seumuran denganku. Bibirnya mungil. Hidungnya kecil tapi proporsional dan sangat menarik. Ia tak berucap apa pun, hanya sedikit tersenyum. Dan, amboi, di balik bibir mungilnya berderet gigi dengan susunan yang rapi bagai kelasi kapal perang berbaris. Putih dan berjejer rapi.
Gadis manis putri Koh Aseng inilah yang belakangan menjadi gadis impianku. Gadis yang membuatku berharap agar ulat-ulat kecil di dalam rongga mulutku berebut menggerogoti gigiku. Gadis yang membuat sakit gigi yang biasanya menyiksa menjadi begitu romantis rasanya. Bahkan berkali Mak ku ajak mengantarkanku ke tempat Koh Aseng dengan alasan gigiku sakit. Padahal aku hanya ingin melihat sekilas gadis “Kopingho” itu menyembul di balik tirai pintu. Cinta memang gila ternyata.
Dan tiga hari yang lalu, setelah sepuluh tahun aku memupuk angan dan impian. Butuh sewindu lebih mengumpulkan keberanian. Dia menolakku.
Bukan cuma penolakannya yang menyakitkan, namun perkataannya yang tak sanggup aku lupakan.
Gadis dengan bibir mungil itu ternyata punya bakat sumpah serapah luar biasa. Bahkan aku, seorang anak kampung yang besar di lingkungan pasar tak pernah berkata sekasar itu. Aku berfikir mungkin sesekali harusnya mulut Amel lah yang harus diberi lotion, biar halus, jangan cuma tangan dan kakinya saja.
Tiga malam lamanya mataku tak mau terpejam. Rasa cinta itu kini telah menjadi dendam. Dan kau Amel, aku benci kamu. Bukan karena penolakanmu. Tapi aku benci karena aku tak mampu melupakanmu.
Siang tadi aku bersama Udin sahabatku pergi ke daerah Congkiong, menemui seorang dukun. Nalarku telah mati. Kinilah saatnya. Cinta ditolak Dukun Bertindak.
Semua bahan yang disyaratkan sudah kusiapkan. Sisa potongan kain kafan, kembang tujuh warna, kumbang Sijontu –aku tak tahu apa bahasa Indonesianya– dan sebongkah menyan serta benang 3 warna.
Aku juga sudah menghapalkan mantera yang kutuliskan pada selembar kertas yang harus kurapal 40 kali di tengah malam, bertelanjang dan berdiri menghadap ke Utara.
“Ingsun matak ajiku si semar mesem, mut-mutaku inten cahyane manjing pilinganku kiwa lan tengen, sing nyawang kegiwang, apa maneh yen sing nyawang kang tumancep kumanthil ing telenging atiku ya iku si jabang bayi “Amel” teka walas teka asih saking kersaning Allah, laillaha ilallah muhammad rasulullah”
Gila bukan?
Tapi ada satu hal yang membuatku pusing tujuh keliling. Ternyata syaratnya belum lengkap. Masih ada satu syarat lagi. Sebuah jarum yang patah.
Dukun Bedebah. Aku misuh sendiri dalam hati. Kemana aku harus mencari sebuah jarum yang patah malam ini. Sementara waktu terus bergerak dan aku belum juga menemukan jarum patah itu.
Sial. Benda kecil dengan pantat berlobang tempat benang ditambatkan itu ternyata sulit dicari.
Jarum, benda kecil berbentuk selindris berujung lancip ini ternyata susah dicari. Jangankan yang patah, yang tak patah pun sulit ditemukan.
Benda kecil yang selalu terabaikan dan kadang gak penting banget. Ia baru diingat ketika pagi senin saat akan berangkat ke kantor, ketika kancing baju melarikan diri karena tak sanggup melawan tekanan perut yang berontak.
Waktu telah lewat tengah malam, dan jarum patah itu tak jua dapat kutemukan. Gagal aku melakukan ritual memelet putri tidurku.
“Selamat kau malam ini Amel…” ujarku geram.
(***)