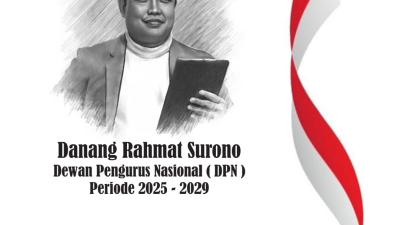Oleh : Agus Sutawijaya.
(CIO) — Budiman tumbuh sebagai anak yang sangat dimanja. Kehendak didapat, pintak belaku. Terlambat ia minta, barang yang diinginkannya telah dibelikan. Pakaiannya selalu saja baru. Baju mengajinya dijahit khusus oleh Ocu Mulis, penjahit kenamaan kampung kami. Bajunya model baju koko, lengkap dengan setelan celananya dengan warna senada. Pecinya hitam mengkilat, “Ini peci Gumarang, dibeli abah di Bukit Tinggi” pamernya pada kami semua saat mengaji di Surau Ujuong. Kami semua hanya mengangguk saja, tak tahu apa itu Peci Gumarang dan tak tahu di mana itu Bukit Tinggi, bagi kami, bukit selalu tinggi, kalau tak tinggi namanya “munggu”.
Tapi kami tahu bedanya peci milik Budiman dengan peci kami. Peci Budiman sangat indah, bulu-bulu hitamnya mengkilat. Bentuknya juga gagah, jantan dan kokoh. Jauh berbeda dengan peciku yang penyok pada bagian depannya, dan tepos bagian belakangnya. Beludrunya juga sudah mulai rontok, persis kucing terkena penyakit kurap. Ini adalah peci warisan mendiang Uwo Dowi, abangku. Peci ini dihadiahkan Mamak Ijun untuk Uwo saat ia disunat. Kata Mak Ijun, peci ini dibelinya di Selat Panjang, saat pulang dari Malaysia.
Sebegitu jeleknya peciku, lebih mengenaskan lagi peci yang dipakai Suntuong teman kami. Pecinya sudah tak lagi jelas bentuknya, jika umumnya peci berbentuk bulat silindris atau lonjong elips, dan mengikut bentuk kepala ketika digunakan, peci Suntuong justru lebih mirip “detau”, peci yang dipakai ninik mamak. Menumpuk dan miring di kepalanya yang “tungka”. Itu jugalah yang menjadi sebab namanya dipanggil Suntuong, singkatan dari “Muhlisun Tungka”.
Memang salah satu kebiasaan orang kampung kami adalah memberikan gelar atau panggilan kepada kawan sebaya. Gelar bisa saja berdasarkan keadaan fisik, cara berjalan, asal dusun, atau apa saja. Tak ada pakem tertentu dalam memberikan gelar atau sebutan untuk panggilan. Hal ini merupakan kebiasaan sejak dahulu, tak tahu siapa yang memulai. Ini, bisa jadi karena di kampung kami terlalu banyak anak yang memiliki nama yang sama. Mungkin orang tua kami bingung harus memberi nama siapa buat anak-anaknya yang hampir setiap tahun sekali lahir, jadi kebanyakan nama kami bersamaan. Contoh saja namaku Iwan, kalau tak salah ada sembilan orang bernama Iwan yang sebaya denganku. Dan orang akan bisa langsung membedakan Iwan yang mana dari gelar panggilannya saja.
Contohnya aku dipanggil Iwan Bincik, karena postur tubuhku paling kecil dari sembilan Iwan lainnya. Ada Iwan Bocek, karena kakinya yang kering dan bersisik persis ikan Bocek atau ikan Gabus. Ada Iwan Jangek, dipanggil seperti itu karena ayahnya adalah tukang pembuat kerupuk Jangek atau kerupuk kulit. Ada lagi Iwan Togai, dipanggil togai karena ia yang paling tinggi. Begitulah salah satu kebiasaan yang jadi ciri khas kampung kami. Yang paling kasihan adalah Iwan Tuyuok. Ia digelari Tuyuok karena waktu lecil dulu telinganya Batuyuok. Tuyuok itu adalah penyakit infeksi telinga, yang menyebabkan telinga bernanah dan baunya…. luar biasa. Meski kini telah sembuh, namun gelar itu telah terlanjur melekat padanya.
Hampir semua keluarga di kampung kami adalah keluarga besar. Rata-rata setiap rumah memiliki 5 sampai 9 orang anak, bahkan ada yang sampai 13 orang anaknya. Orang kampung kami tak mengenal KB, sehingga setiap hari selalu saja ada bayi yang di tolong kelahirannya oleh Niok Losun, satu-satunya dukun beranak di kampung kami. Ia juga yang nanti akan menindik dan mengkhitan bayi perempuan kampung kami. Sedang untuk anak lelaki, ada Tuok Salio yang akan merubah bentuk dan menasbihkan kelelakian kami. Hampir semua lelaki di kampung kami adalah korban mutilasi Tuok Salio. Makanya, selain dihormati sebagi Imam, beliau mendapat posisi tinggi di mata masyarakat kami. Bagai mana tidak, semua anak lelaki, pada suatu ketika pasti akan berhadapan dengannya. Duduk bersimpuh di atas batang pohon pisang setelah berendam sejak sudah subuh di tepian, dan akan bersiap menerima takdir untuk menerima bentuk baru seumur hidup. Tak ada yang berani melawan titah Tuok Salio, takut nanti waktu disunat, malah dibuang semua itu “titit” oleh Tuok Salio.
Keadaan kami semua di kampung hampir sama susahnya. Ayah kami rata-rata hanyalah penyadap karet di Daek –rimba. Mak kami membantu dengan berladang. Unik memang, di kampung kami berladang itu dikerjakan ibu-ibu. Mungkin begitulah cara tetua kami bekerjasama dalam keluarga. Ayah yang mencari uang untuk semua kebutuhan dan Mak kami yang bertugas menangani persediaan pangan. Keadaan kehidupan kami rata-rata, maka semua yang ada pada Budiman selalu tampak mencolok dan beda.
Budiman adalah satu-satunya seingatku orang yang tidak dipanggil dengan sebutan atau gelar. Tentu saja, karena nama Budiman hanya satu-satunya, dan bagi kami masih aneh aja mendengar nama Budiman di antara nama Tojik, Mulis, Osue, Man, Pidau, Sude, Sobi atau Canga. Namanya berkelas.
Begitu juga semua yang dipakainya. Ketika pergi mengaji, semua anak membawa suluo, yaitu obor yang terbuat dari ikatan daun kelapa kering, maka Budiman adalah satu-satunya anak yang membawa senter. Senternya bagus, berkilat, dengan dua baterai. Ada gambar kepala Harimau di bagian belakang penutup tempat baterainya dan terpahat tulisan TIGER. Kalau kepala senter itu diputar saat dinyalakan ke arah dinding, akan tampak sebuah titik fokus berwarna kuning, semakin diputar ke kiri fokusnya makin melebar dan titik kuning tadi berubah menjadi sebuah lingkaran yang bertambah besar, demikian sebaliknya. Jika di sepanjang jalan kami harus mengibas-kibaskan suluo kami agar tetap menyala, maka Budiman hanya menekan sebuah tombol berwarna merah di badan senternya.
Sendal yang kami pakai biasanya adalah sendal jepit karet bermerk Swallow. Sendal itu dibeli lebaran tahun lalu, dan harus ada sampai lebaran tahun depan, bagaimana pun caranya. Kalau putus, biasanya pada bagian tali yang dijepit jempol dan telunjuk kaki, maka kami akan menyambungnya dengan tali, atau menusukkan peniti pada bagain tapaknya. Hampir semua sendal kami sama kecuali tentu saja sendal Budiman. Ia selalu memakai sendal Lily yang mengkilat. Warnanya juga senada dengan baju yang dikenakannya.
Tentang masalah makanan kami pasti lebih jauh lagi bedanya. Kalau pergi Sekolah Petang, biasanya kami membawa bekal nasi makan siang kami tadi. Kami biasa memasukkan nasi ke dalam kantong plastik dengan lauk seadanya, tak jarang kadang hanya nasi dan minyak goreng lado saja. Sementara Budiman, jangan ditanya. Jika kami makan dengan lauk salai, maka Mak kami hanya mampu membeli salai ikan Motan, kadang itu pun tak dibeli, tapi hasil pancingan ayah di tepian yang diletakkan Mak di atas Salayan atau para-para di atas tungku. Budiman, ikan salainya pasti saja Ikan Silai yang besar. Ikan ini terbuat dari Ikan Selais yang harganya mahal, dan berasal dari daerah Bunut sana, kami pun tak tahu Bunut di mana. Kalau kami makan ikan Pitulu, maka Budiman pastilah Ikan Lomak. Kalau Mak kami masak goreng ikan Katuong, maka Mak Budiman masak ikan Kalui. Mak kami masak ikan Patin, maka lauk Budiman pastikan ikan Tapah. Semua yang Budiman miliki selalu yang terbaik. Bahkan, saat lebaran, kalau di rumah Budiman, rendangnya itu terbuat dari daging Kerbau yang empuk sekali. Di rumah kami paling banter rendang Itiok Suwati, atau Mentog, itu pun dengan tambahan potongan singkong yang digoreng terlebih dahulu, dan lebih banyak Singkongnya dari pada daging Itiok Suwatinya.
Tapi kami senang dengan Budiman, berteman dengannya membuat kami bisa mencicipi paling tidak tahu bagai mana rasa makanan yang lezat itu walau hanya secuil. Dan itu sebenarnya tidak gratis juga, karena kami sering kali harus diperbudak olehnya. Budiman tumbuh jadi anak yang semua kemauannya harus dituruti. Jadilah kami semua teman-temannya menjadi abdi bagi Budiman yang menasbihkan diri sebagai tuan. Kalau bermain, maka Budiman tak pernah boleh kalah, ia harus selalu menang. Kalau sempat ia kalah, atau tak senang ia akan menangis dan mengadukan halnya pada Toke, dan kami semua akan diomeli Toke. Bukan cuma kami, ayah-ayah kami pun akan diomeli Toke, sebab menurutnya kami telah jahat pada Budiman. Tentu saja sesampai di rumah, kami semua akan menerima omelan dari ayah.
Bukan sekali dua kali Budiman membuat masalah di kampung. Selalu saja ada keonaran yang diciptakannya. Dan selalu saja Toke membela anak semata wayangnya itu. “Barang nan rusak digonti, nan sakik diubek, apo payah…” begitu ucapnya ketika ada yang mengadukan kenakalan Budiman pada Toke.
Dalam setiap kesempatan Toke selalu membanggakan anaknya pada ayah atau ibu kami. “Budiman tu isuok akan jadi dokter, dr Budiman, kalau kalian sakit nanti dia yang mengobati, jan jahek anak kaliàn ke Budiman” ucapnya sambil memberikan beberapa lembar uang dan mencatatnya di sebuah buku sebagai pinjaman yang akan dibayar hari Jumat saat “mambangkin” atau panen getah.
Budiman telah menjadi sosok “Raja” kecil di kampung kami. Sebenarnya warga di kampung benci melihat perangainya, tapi tak ada seorang pun yang berani menegur karena takut kepada Toke. Toke adalah boss di kampung, kepadanya orang kampung berhutang ketika duit tak ada. Kepadanya pula warga menjual hasil pertaniannya.
(***)